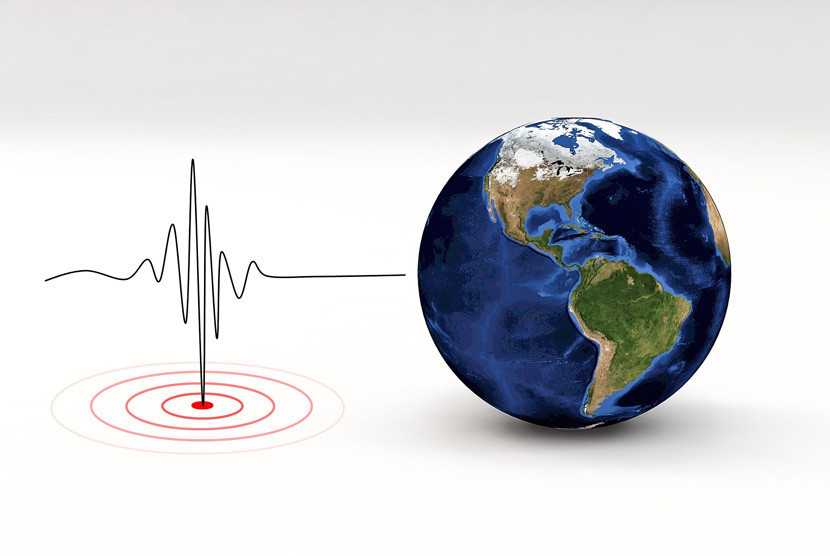Masjid: Benteng Kemanusiaan di Tengah Bencana Sumatera Barat

Febrin Anas Ismail dan M Afarisi Farhan
Fakultas Teknik Unand
“Alam tak pernah kompromi, tetapi manusialah yang dituntut untuk lebih bijak bersiap.” Kalimat itu sering saya ulangi setiap kali berbicara tentang bencana di Sumatera Barat. Kita hidup di tanah yang indah—gunung, laut, dan lembah berpadu membentuk lanskap memukau—namun sekaligus rapuh karena berdiri di atas pertemuan lempeng yang terus bergerak.
Sejarah mencatat, gempa dan tsunami bukan sekadar ancaman, melainkan bagian dari denyut kehidupan yang terus berulang sejak abad ke-18. Setiap kali bumi bergetar, bayangan gelombang besar kembali menghantui, terutama bagi mereka yang tinggal di pesisir Padang, Pariaman, hingga Pesisir Selatan. Inilah wilayah “zona merah”, yang dalam skenario terburuk hanya punya waktu tiga puluh menit untuk menyelamatkan diri setelah gempa besar. Dalam situasi sesingkat itu, setiap detik benar-benar menjadi penentu hidup atau mati. Membangun shelter evakuasi adalah jawaban logis, tetapi implementasinya tidak sesederhana menekan tombol.
Realitas di lapangan membuat kita dihadapkan pada jalan buntu: lahan kosong sulit dicari, permukiman padat menutup ruang alternatif, sementara anggaran pemerintah terbatas dan sering tersendat oleh prioritas lain. Pertanyaannya, apakah kita akan terus menunggu gedung evakuasi yang mahal dan jauh dari jangkauan warga? Atau kita mencari solusi yang lebih membumi, dekat dengan masyarakat, sekaligus selaras dengan budaya lokal?
Di sinilah masjid hadir sebagai alternatif yang masuk akal sekaligus menyentuh hati. Masjid bagi orang Minangkabau bukan sekadar bangunan untuk shalat berjamaah. Ia adalah pusat kehidupan sosial: tempat anak-anak belajar mengaji, warga bermusyawarah, hingga menjadi titik temu dalam keseharian.
Hampir setiap nagari memiliki masjid, dan kedekatan emosional ini adalah modal sosial yang sangat kuat. Dalam konteks mitigasi bencana, masjid bisa menjadi lebih dari ruang ibadah—ia dapat menjelma sebagai benteng keselamatan jiwa.
Bayangkan sebuah skenario: gempa besar mengguncang, listrik padam, warga berlarian. Di tengah kepanikan itu, pengeras suara masjid bukan hanya memanggil jamaah, melainkan menjadi alarm darurat: “Segera evakuasi ke masjid, lantai atas siap menampung.”
Menara masjid yang biasanya menandai arah kiblat kini berfungsi ganda sebagai menara sirine. Arahan itu tidak asing di telinga warga, karena masjid adalah tempat yang sudah akrab. Mereka tahu jalannya, tahu pengurusnya, tahu bahwa ruang di atas bisa menyelamatkan mereka.
Tentu, menjadikan masjid sebagai shelter bukan sekadar menempelkan label “aman” pada dindingnya. Butuh perencanaan infrastruktur yang matang. Dari kacamata teknik sipil, beberapa prinsip penting harus diperhatikan.
Pertama, lantai bawah masjid sebaiknya dirancang terbuka agar air tsunami bisa lewat tanpa merusak struktur utama. Kedua, fondasi dan rangka harus diperkuat dengan standar ketahanan gempa, seperti pedoman FEMA P-646 atau PPTGI 2019. Ketiga, akses tangga dan jalur evakuasi harus lebar, aman, dan ramah bagi semua kelompok—anak-anak, lansia, hingga penyandang disabilitas. Lantai atas perlu disiapkan sebagai ruang perlindungan dengan kapasitas memadai, minimal satu meter persegi per orang. Dalam keseharian, ruang itu bisa digunakan untuk kegiatan sosial atau pendidikan, dan ketika bencana datang, ia berubah fungsi menjadi rumah selamat. Apa yang menarik dari konsep ini adalah sifatnya yang sederhana tapi menyelamatkan nyawa.
Kita tidak bicara tentang proyek raksasa bernilai miliaran, melainkan penguatan fungsi bangunan yang sudah ada. Setiap kampung punya masjid, dan jika masing-masing dipersiapkan dengan baik, maka kita sesungguhnya sedang membangun jaringan perlindungan yang tersebar dan akrab di hati warga. Di sinilah keunggulannya dibanding shelter konvensional.
Masjid bukan gedung asing. Ia adalah ruang dengan rasa memiliki yang tinggi. Warga sudah terbiasa berkumpul di sana, bahkan dalam kondisi gelap sekalipun. Karena itulah evakuasi ke masjid bisa lebih cepat, teratur, dan minim kebingungan.
Namun gagasan ini tidak boleh berhenti di atas kertas. Kita perlu memastikan bahwa masjid yang dirancang sebagai shelter benar-benar memenuhi standar keselamatan. Pemerintah daerah dan BPBD harus hadir sebagai pengarah teknis, perguruan tinggi memberikan kajian dan desain, sementara LSM serta media lokal membantu edukasi dan advokasi.
Di sisi lain, peran Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta maupun BUMN juga menjadi kunci. Program CSR bukan semata kegiatan filantropi, tetapi dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur kesiapsiagaan, mulai dari pengadaan peralatan Early Warning System (EWS), penyediaan panel surya, hingga pencetakan modul edukasi kebencanaan.
Banyak perusahaan besar—baik yang bergerak di sektor energi, perbankan, maupun telekomunikasi— sesungguhnya punya alokasi CSR yang dapat disinergikan dengan kebutuhan nyata masyarakat pesisir. Jika perusahaan dan pemerintah bisa duduk bersama, masjid sebagai shelter akan lahir bukan hanya dari dana penelitian, tetapi juga dari tanggung jawab sosial kolektif dunia usaha. Yang lebih penting lagi, pengurus masjid dan jamaah harus dilibatkan sejak awal. Shelter bukan proyek instan yang datang dari luar, melainkan hasil kesepakatan warga yang merasa memiliki.
Dengan kombinasi dukungan teknis pemerintah, pengetahuan akademisi, pendampingan LSM, dan kontribusi CSR perusahaan, rasa memiliki itu akan tumbuh lebih kuat. Masjid akan berdiri bukan hanya sebagai ruang ibadah, tetapi juga simbol kolaborasi banyak pihak dalam menjaga kehidupan.
Satu hal lain yang tak boleh diabaikan adalah latihan rutin. Infrastruktur sehebat apapun akan sia-sia bila masyarakat tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Karena itu, simulasi evakuasi harus menjadi tradisi baru.
Bayangkan setiap selesai pengajian atau acara remaja masjid, warga berlatih jalur evakuasi: anak-anak digandeng, lansia dituntun, jalur kursi roda dipakai. Semakin sering dilatih, semakin kecil peluang panik saat bencana datang. Tubuh dan pikiran akan terbiasa, sehingga keputusan bisa diambil lebih cepat dan lebih banyak nyawa terselamatkan.
Saya melihat, konsep ini juga menyatukan dua hal yang sering dipisahkan: iman dan ilmu. Masjid tetap menjadi pusat spiritual, tempat manusia bersujud kepada Sang Pencipta. Tetapi di saat bersamaan, ia adalah simbol ikhtiar—ruang yang dirancang dengan ilmu pengetahuan untuk melindungi umat.
Pesannya jelas: iman tidak berarti pasrah tanpa usaha, justru iman menguatkan ikhtiar. Dengan menjadikan masjid sebagai shelter, kita sedang menyatukan nilai agama, budaya gotong royong Minangkabau, dan teknologi mitigasi modern dalam satu tarikan nafas.
Apakah gagasan ini sempurna? Tentu tidak. Ada tantangan besar yang perlu diantisipasi. Pertama, masjid punya fungsi utama sebagai ruang ibadah. Penyesuaian desain harus dilakukan dengan bijak, menghormati kesakralan. Kedua, perawatan jangka panjang tidak boleh diabaikan. Shelter bukan bangunan sekali jadi, melainkan harus terus dijaga dan diperbarui. Ketiga, komunikasi intensif dengan tokoh agama dan masyarakat mutlak diperlukan agar tidak terjadi resistensi.
Namun jika semua hambatan itu diatasi dengan keseriusan, sulit untuk menyangkal bahwa masjid adalah pilihan paling realistis. Kita tidak bisa menghindari ancaman gempa dan tsunami di Sumatera Barat. Tetapi kita bisa memilih cara untuk lebih siap. Masjid sebagai shelter mandiri bukan sekadar ide romantis, melainkan strategi yang lahir dari realitas sosial dan kebutuhan nyata masyarakat pesisir.
Dengan komitmen bersama, ia bisa menjelma menjadi jaringan perlindungan yang nyata, menyebar di setiap kampung, mengakar di hati warga. Ketika bumi berguncang dan laut mengamuk, masjid akan berdiri bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi sebagai saksi ikhtiar manusia menjaga kehidupan. Pada saat itu, doa dan tindakan bersatu dalam ruang yang sama—dan barangkali, itulah makna terdalam dari keselamatan yang kita cari dunia dan akhirat.(*)